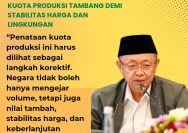Radarnesia.com – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 135/PUU-XXI/2023 menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.
Pemilu nasional; Pilpres, DPR, dan DPD, akan digelar pada 2029. Sementara pemilu lokal; pilkada dan pemilihan DPRD, dilaksanakan paling lambat 2,5 tahun setelahnya.
MK menilai model serentak lima kotak seperti 2019 dan 2024 terlalu kompleks: membebani penyelenggara, menghambat kaderisasi partai, menyebabkan kejenuhan pemilih, meningkatkan suara tidak sah, serta menenggelamkan isu lokal akibat dominasi kontestasi nasional.
Mahkamah berpendapat, apabila pemilu borongan seperti ini terus dibiarkan dapat mengancam kualitas demokrasi.
Keputusan MK tersebut kemudian menimbulkan perbincangan ramai di publik. Paling tidak terdapat tiga persoalan dari keputusan tersebut.
Pertama ialah legalitas keputusan MK, yang dipandang telah melebihi ruang yudikatif sebab teknis pelaksanaan pemilu bersifat open legal policy, yang menjadi ranah pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah.
Kedua, pemisahan pemilu nasional dan lokal akan melanggar Pasal 22E UUD 1945 tentang siklus pemilu lima tahunan.
Kemudian yang ketiga ialah masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Jika keputusan MK dilaksanakan, maka akan terjadi kekosongan di seluruh daerah, sebab kepala daerah dan anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2024 sudah habis masa jabatannya pada 2029, sementara pemilu lokal baru akan dilakukan pada 2031.
Lantas bagaimana semestinya memaknai putusan terbaru MK tersebut? Para ahli dan pakar hukum mungkin memiliki pandangannya tersendiri, namun pada akhirnya semua akan bersepakat bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, mematuhi keputusan mahkamah bukan sesuatu yang bisa ditawar.
Perlu ditambahkan pula di sini bahwa praktek pelaksanaan pemilihan yang keluar dari siklus lima tahunan pernah terjadi. Pengalaman beberapa daerah yang seharusnya melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023 misalnya, baru melaksanakan pemilihan pada 2024. Begitu juga dengan masa jabatan, ada kepala daerah yang menjabat kurang dari lima tahun namun ada juga yang lebih.
Praktek seperti ini dimungkinkan dan tetap konstitusional selama dalam koridor masa peralihan dan diatur dalam undang-undang.
Berkaca dari pengalaman tersebut, memisahkan pemilu nasional dan lokal tidak bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, dalam putusan Nomor 135 mahkamah menyebut “Pembentuk undang-undang diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan mekanisme dan waktu pelaksanaan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, termasuk masa transisi, sepanjang tetap menjamin kepastian hukum dan tidak melanggar prinsip pemilu yang demokratis.”
Kini, wacana mengenai desain atau model transisi yang dimaksud mulai bermunculan, mulai dari penyesuaian masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD agar nantinya sesuai keputusan mahkamah, hingga kemungkinan-kemungkinan lain seperti pemilu sela khusus untuk pemilihan anggota DPRD.
Beberapa Kemungkinan
Sayangnya, partai-partai melalui anggotanya di DPR menunjukkan sikap keberatannya atas putusan MK tersebut. Paul Pierson dalam Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics (2000) memberikan kerangka berpikir tentang bagaimana institusi kepartaian merespon perubahan, baik di dalam maupun di luar dirinya.
Umumnya partai politik cenderung menolak perubahan drastis, termasuk perubahan sistem pemilu, sebab mereka mendapatkan insentif dari sistem lama. Partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra merupakan yang paling diuntungkan dari sistem pemilu lima kotak yang sudah dipraktekkan di 2019 dan 2024.
Dalam dua pemilu terakhir, partai-partai tersebut stabil berada di tiga besar tabel perolehan suara dan kursi DPR. Apabila sistem pemilu tidak berubah, ketiganya masih bisa memproyeksikan peningkatan manfaat (returns) elektoral pada pemilu selanjutnya.
Paling tidak terdapat dua hal utama yang diperkirakan berdampak pada partai-partai politik dari pemisahan pemilu nasional dan lokal.
Pertama ialah hilang atau berkurangnya efek ekor jas terutama pada pemilihan lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada pemilihan serentak, partai peserta pemilu yang bertarung di pileg daerah masih bisa berharap mendapat berkah dukungan dari pemilih yang mencoblos pasangan capres-cawapres yang diusungnya pada Pilpres.
Pun demikian, Pileg DPR RI, para calegnya tidak lagi bisa menggunakan strategi tandem dengan kolega partainya yang maju di pileg lokal di daerah pemilihan yang sama atau beririsan. Dengan kata lain, apabila pemilihan dilakukan terpisah, partai politik perlu memikirkan strategi yang baru.
Kedua, partai politik dipaksa untuk terus melakukan konsolidasi dan mobilisasi pada waktu yang berbeda, yang berarti juga menambah tenaga, biaya dan logistik kampanye. Dalam hal saksi di TPS misalnya, partai perlu menyiapkan anggaran untuk dua pemilihan di waktu yang berbeda, dengan cakupan wilayah yang hampir sama besarnya.
Melihat kecenderungan sikap partai-partai di DPR saat ini, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi terkait pembahasan RUU Pemilu. Pertama ialah skenario ideal, di mana DPR bersama Pemerintah memulai pembahasan RUU Pemilu dengan arah pembahasan sesuai putusan MK.
Dalam skenario ini, partai politik menjadikan ruang pembahasan sebagai arena adu gagasan untuk memastikan partainya tetap diuntungkan dalam sistem pemilu yang baru. Sejarah telah menunjukkan bahwa hanya partai yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan survive (Harjanto, 2023).
Kedua ialah skenario kompromi, di mana UU Pemilu dibuat namun tidak sepenuhnya mengadopsi putusan MK. Dalam skenario ini, pemilu nasional dan lokal dipisah, namun kepala daerah tidak dipilih langsung oleh pemilih, melainkan ditunjuk pemerintah pusat atau melalui DPRD hasil pemilu lokal.
Wacana pemilihan tidak langsung disuarakan oleh beberapa ketua partai, dengan dalih Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebut kepala pemerintah daerah “dipilih secara demokratis”. Padahal, opsi pemilihan tidak langsung sudah tertutup melalui Putusan MK No135 tersebut, sebab MK dengan jelas menggunakan istilah “pemilihan umum” baik nasional maupun lokal.
Kemungkinan berikutnya ialah yang paling buruk, di mana DPR tidak merevisi UU Pemilu, sehingga pemilihan selanjutnya tetap dengan format yang sama dengan pemilu sebelumnya. Alasan yang mungkin akan muncul ialah bahwa apabila putusan MK dijalankan maka DPR akan melanggar UUD 1945 tentang pemilu yang dilakukan setiap lima tahun, atau dengan alasan tidak cukupnya waktu yang tersedia akibat deadlock di antara faksi-faksi di DPR.
Apabila ini yang terjadi, maka skenario terakhir yang bisa diharapkan ialah keluarnya Perppu UU Pemilu oleh Presiden. Sebagai pemimpin, Presiden Prabowo tentu memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kepastian hukum dan melindungi hak demokratik warganya yang tercermin dalam Putusan MK.
Namun mengeluarkan Perppu merupakan indikasi tidak sehatnya kondisi suatu negara karena biasanya hanya dikeluarkan saat darurat atau kegentingan yang memaksa.
Pada akhirnya, putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal harus dipandang sebagai kesempatan untuk menata ulang demokrasi kita secara lebih berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada kualitas.
Harapan tetap terbuka bahwa para wakil rakyat akan mengedepankan kebesaran jiwa dan visi kenegaraan, bukan sekadar kalkulasi elektoral.*) Dimas Ramadhan adalah Peneliti di Populi Center dan menjadi bagian dari Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.